Au Loim Fain, Romi Perbawa
Oleh Kurnia yaumil fajar
“Perjalanan saya menuju kehidupan terdalam para pekerja migran membuktikan bahwa tak ada hal yang tak masuk akal. Bahkan tak ada salah dan benar untuk sebuah alasan kuat yang hanya dirinya sendiri yang paham” – Romi Perbawa
Secuplik teks insani di atas, ada pada pengantar singkat untuk menelusuri lebih dalam perjalanan Romi dalam mendokumentasikan kehidupan para pekerja migran. Dua kalimat yang berkali-kali saya lihat ulang usai membaca buku ini.
Memasuki dua halaman penuh berisi foto pertama, saya dihadapkan pada jalan setapak di dalam hutan. Halaman selanjutnya, masih dengan tampilan dua halaman penuh, pada jalan setapak yang berbeda, terdapat tiga laki-laki bertelanjang kaki. Dua foto pembuka yang menandai sebuah lintasan peristiwa perpindahan. Dari gelap menuju sesuatu yang lebih terang, untuk pergi ataupun pulang. Entah siapa yang pergi, pulang, atau berpulang.
Pada halaman selanjutnya, terdapat catatan singkat tentang siapa yang pergi; ialah para Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya pekerja migran berketerampilan rendah. Sebagai pembuka bagian ini, terdapat foto Kasmini (35), saat tengah beraktivitas di dalam rumah. Kerja mata kita akan segera melihat kata bercetak tebal pada sebuah piagam penghargaan yang berada di kabinet milik majikan Kasmini. Tertulis resilience, yang memiliki arti kapasitas seseorang untuk bertahan dan beradaptasi dalam situasi sulit. Tulisan resilience menjadi sangat kuat pada bagian pembuka, merajut tangkapan visual lain di mana potret para pekerja migran berada di lingkungan kerjanya.
Bagian awal ini ditutup dengan foto Maria (16) yang tengah berlari tergesa di dalam rumah, sembari membawa gantungan pakaian. Maria mengenakan jepit dan bandana di rambutnya yang ikal. Potret Maria berlari bersanding dengan keterangan: “Malaysia telah menetapkan aturan bahwa usia minimum untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah 21 tahun.” Menatapi keduanya, teks-foto, Maria seolah berlari dari aturan. Maria berlari melampaui usianya. Maria, berlari di antara teman sebayanya yang sedang bersekolah. Maria, berlari dari kenyataan bahwa besar kemungkinan untuk tertangkap dan pulang. Namun satu hal yang pasti, Maria sedang berlari untuk “bertahan”.
Selanjutnya tentang sebagian hal yang dialami para pekerja migran: mengikuti pelatihan, membuat pilihan untuk pergi, melakukan perjalanan, berada dalam transit, pulang, atau bersembunyi. Foto pertama, saya tertuju pada dua perempuan muda yang keduanya mengenakan hiasan di kepala, sama seperti Maria. Mereka tengah melakukan pelatihan, yang saya tebak ini adalah pelatihan bahasa di wilayah mereka akan ditempatkan. Melakukan pelatihan adalah salah satu tahapan yang harus dijalani calon pekerja migran legal. Dua foto selanjutnya menampakkan situasi padatnya pelabuhan transit dan pelabuhan tujuan. Lalu tentang Rusmayanti (25) yang sedang berada di dalam bus travel bersama dua orang lain. Matanya menerawang ke luar jendela, ia terpaksa meninggalkan anaknya yang baru berusia 7 bulan untuk menjadi pekerja migran di Taiwan. Suasana sedu tak terelakkan. Halaman selanjutnya menceritakan tentang Roslinda (40). Ia bersama dua anaknya berada di gubuk kecil dengan cahaya temaram. Berdasarkan keterangan, mereka bersembunyi dari polisi dan petugas imigrasi Malaysia. Pada bagian ini, saya merasa Romi tengah menggeser cara melihat saya terhadap para pekerja migran yang ia temui. Dengan kehadiran anak-anak dalam foto, mereka tidak lagi hanya dilihat sebagai seorang individu dewasa yang sedang menempuh jalan sebagai pekerja migran, melainkan juga sebagai sosok orang tua.
Terlempar pada tahun 2012, ihwal yang mengawali Romi Perbawa melakukan perjalanan ini, adalah pertemuannya dengan Arnoldus Karno Rico, seorang nelayan cilik dari Desa Iniere, Aimere, Nusa Tenggatara Timur. Karno ditinggal oleh kedua orangtuanya yang menjadi pekerja migran sejak usia 6 tahun. Di tepi kapal Karno berdiri menghadap laut lepas. Di foto lain Karno tertidur meringkuk di atas kapal. Cahaya matahari cukup keras membentuk bayangan di dekat Karno. Setelah melihat Karno dari punggung dan sisi, Romi menampilkan potret Karno dari dekat. Anak berusia 13 tahun itu menatap tajam ke arah saya melalui lensa kamera Romi. Sinar matahari jatuh di samping tubuhnya, menegaskan terang dan gelap pada lengan, pundak, tulang selangka, dan dada.
Karno adalah satu dari begitu banyak anak pekerja migran. Romi menemui beberapa di antara mereka. Romi menyusun halaman demi halaman dengan cermat, memberi setitik pernyataan dari berbagai tempat. Seperti halaman foto anak-anak yang tinggal di kampung halaman, lalu kita lihat seorang migran Hong Kong tengah mengurus anak majikannya. Kemudian anak-anak yang lahir di negeri seberang, dilanjutkan dengan foto anak-anak yang berada di kongsi dan tidak memiliki akses pendidikan. Seolah mengajak saya untuk berpikir tentang betapa tidak pastinya nasib yang didapat anak-anak ini kelak.
Rangkaian foto selanjutnya memberi perhatian menyoal para pekerja migran yang dideportasi. Sekumpulan orang membuat barisan, di depan mereka seorang berseragam loreng tengah memeriksa isi dompet para pekerja migran yang akan dideportasi. Keduanya, baik pekerja migran maupun aparat penegak hukum, menunduk. Foto setelahnya tentang anak-anak yang berada di PTS (Pusat Tahanan Sementara). Juga sosok ibu yang tengah menggendong anaknya yang berusia 3 bulan. Menurut keterangan, ia ditangkap saat sedang hamil 5 bulan. Bagian ini ditutup dengan 8 foto potret para pekerja migran perempuan yang dideportasi. Mereka sedang membuat pasfoto untuk pembuatan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Surat ini adalah bagian dari administrasi yang harus ditempuh agar dapat pulang ke Indonesia. Romi memilih untuk menampilkan hasil invert dari foto mereka. Menghasilkan foto-foto serupa film negatif. Kerja visual ini serupa sensor yang memperkuat anonimitas dari para pekerja migran. Tanpa nama, tanpa identitas, hanya dikenali sebagai tahanan imigrasi.
Saya sempat menghubungi seorang teman bernama Eka Putra Nggalu yang tinggal di Flores, memintanya untuk bercerita tentang pekerja migran. Saya menanyakan perihal Adonara, tempat yang beberapa kali muncul di dalam buku Romi. Ia bercerita, ada semacam pemahaman yang diyakini di sana, “Ada satu tempat, satu surga di luar, yang menjanjikan hidup lebih baik. Itulah kepercayaan Kinabalu. Kata Kinabalu itu seperti kata merantau begitu. Semacam cerita turun-temurun, sehingga jadi harapan kolektif. Saya sempat berada satu forum dengan Maximus Masan Kian (seorang guru di Solor) saat ia menceritakan soal itu.” Kami mengobrol banyak malam itu, tentang perekrutan yang seringkali dari keluarga sendiri, tentang satu daerah yang masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu, tentang cara berpakaian pekerja migran sukses, hingga musik-musik dangdut yang mereka bawa. Ia pun bercerita, untuk wilayah Flores Timur dan Timor, kebanyakan pekerja migran yang berangkat itu laki-laki. Mereka bekerja di industri atau perkebunan kelapa sawit. Menjawab pertanyaan saya pada dua foto yang membuka bagian tentang deportasi.
Perihal pulang ke kampung halaman, Romi membuka bagian ini dengan foto seorang Ibu yang sedang memeluk erat anaknya di bandara, setelah 9 tahun berpisah. Halaman selanjutnya, kepulangan yang lain, sebuah peti jenazah sedang dibawa oleh banyak orang. Foto selanjutnya, di dalam ruangan, seorang Ibu dan anak kecil tengah bersandar pilu pada peti, peti jenazah Adelina J. Sau.
Pada tahun 2018, Adelina J. Sau meninggal dunia. Kalimat terakhir yang diucapkan Adelina menjadi judul buku ini: “Au Loim Fain” yang berarti “Aku Ingin Pulang”. Adelina meninggal pada usia 20 tahun, satu hari setelah diselamatkan. Selama 2 tahun ia bekerja tanpa bayaran dan disiksa oleh majikannya, Ambika MA Shan (61). Adelina lahir pada tahun 1998, usianya dipalsukan oleh calo yang mengirim dirinya ke Malaysia guna memenuhi aturan. Berita lain mengabarkan, majikan Adelina dibebaskan oleh Pengadilan Banding Malaysia. Keputusan ini banyak sekali menuai gugatan, pertanyaan, juga kekecewaan. Menjadikan kalimat terakhir dari Adelina sebagai judul buku, bagi saya pribadi adalah salah satu bentuk upaya seorang sipil, Romi Perbawa, untuk memaknai kematian Adelina.
Memasuki bagian akhir buku, dalam foto terdapat Rizkiyah (13), berlari membawa sebungkus kopi instan di antara semak belukar. Foto selanjutnya masih tentang Rizkiyah, ia berada di dalam rumah bersama neneknya. Kemudian Rizkiyah, dengan tubuhnya yang mungil sedang menjemur genteng. Foto terakhir tetang Rizkiyah, juga foto yang menjadi halaman selimut buku ini, adalah sosok Rizkiyah yang tengah melipat kedua tangannya di depan dagu. Seperti orang dewasa yang sedang berfikir. “Aku akan mengusir ibuku ketika dia pulang. Dia tidak boleh tinggal di rumah ini,” tertulis pada sisi buku. Entah apakah bisa disebut kemarahan, ketika anak harus bekerja dan tinggal bersama extended family. Absennya sosok orang tua menjadi permasalahan anak pekerja migran, masalah yang lain, datang dari dua foto setelahnya. Anak-anak yang mengalami pemerkosaan, persoalan remaja, tapi ada pula anak-anak yang beruntung untuk menggunakan remitan dari orang tua yang bekerja di luar untuk memenuhi pendidikan mereka. Dari susunan foto-foto anak yang Romi temui, saya melihat bagaimana nasib seorang anak pekerja migran dapat begitu berbeda satu dengan yang lain.
Sekilas saya teringat gambaran tentang TKI yang disiksa dengan benda-benda domestik. Ketika setrika, sapu, teko, beralih fungsi menjadi senjata. Gambaran itu saya dapat dari berita-berita yang sekadar lewat saja. Berita tentang Pekerja Migran Indonesia tidaklah sebanyak berita-berita pembangunan dan berita politik lain. Ironi, mengingat Indonesia masih melihat mereka sebagai pahlawan devisa. Lewat buku ini, saya diajak untuk melihat lebih banyak. Terlebih mendapati hal yang lebih jarang lagi saya ketahui, lapis dua permasalahan besar yang bertaut dengan isu Pekerja Migran Indonesia, yakni perihal keluarga, khususnya anak-anak dari para pekerja migran. Betapa tidak terlepasnya relasi anak dan orangtua sehingga perlu untuk memberi perhatian pada hal tesebut. Buku ini, buku yang berisi foto dokumenter yang Romi kerjakan, cukup membuat saya kelelahan, tidak hanya soal apa yang saya lihat dan baca di dalam buku, tetapi juga gangguannya terhadap gambaran-gambaran tetang pekerja migran yang selama ini saya miliki.
Akhir kata, saya berdoa semoga ada titik terang perihal permasalahan yang dihadapi anak pekerja migran, di mana pun mereka berada. Terima kasih untuk Romi Perbawa yang dengan tabah mengerjakan buku ini, juga tim yang mendukung. Saya kerap bertanya, apa yang mendorong seseorang untuk membuat foto dokumenter. Terlebih ketika saya tahu Romi tidak bekerja sebagai jurnalis media. Menandai Romi sebagai seorang fotografer amatir yang mengerjakan dokumenter seperti ini—juga Riders of Destiny, mungkin tidaklah relevan. Namun yang pasti, kepekaan Romi sebagai seorang anak yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi anak-anak di Indonesia perlu saya kagumi. Pun mempertanyakan alasan Romi untuk mengerjakan proyek fotografi ini mungkin dapat pula dijawab oleh pernyataan yang saya kutip di awal, tentang tak ada hal yang tak masuk akal untuk sebuah alasan kuat yang hanya dirinya sendiri yang paham. *salim virtual
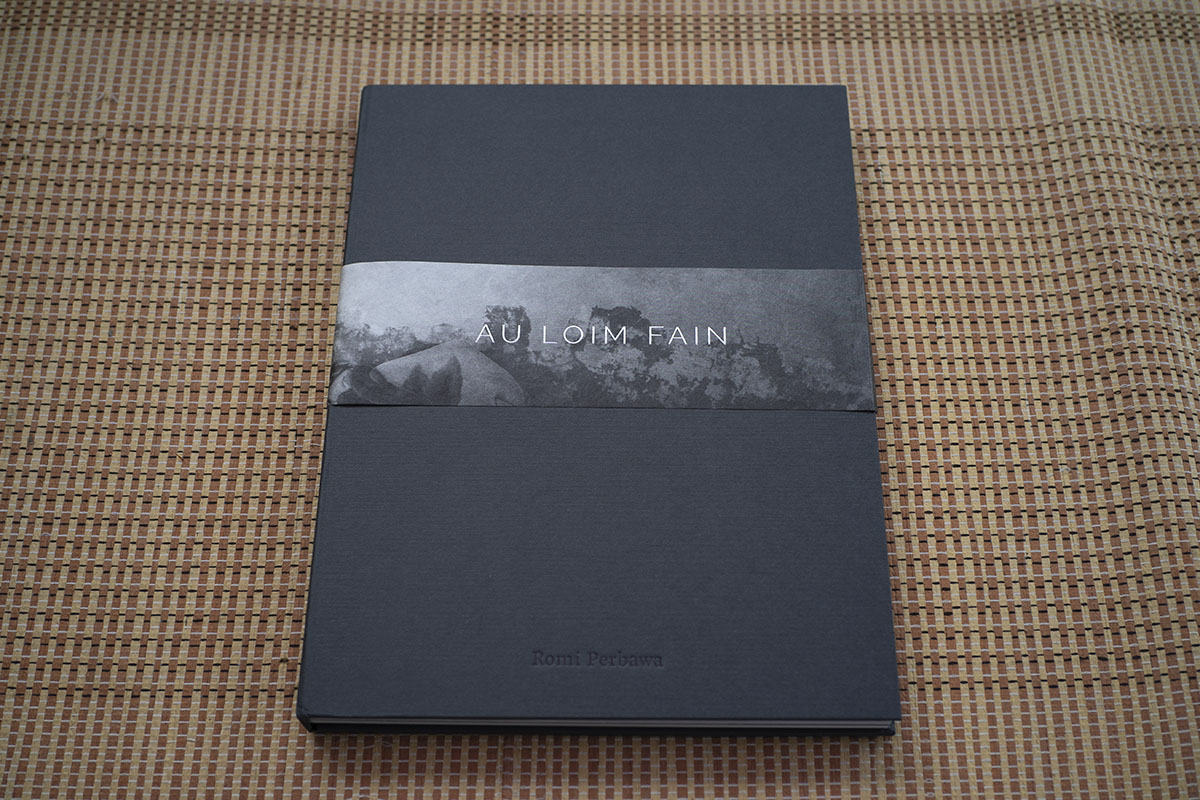
Informasi tentang buku Au Loim Fain bisa dilihat di sini.






