Fotografi dan Terapi dari Kacamata Seorang Pengajar
Oleh Abimanyu Dirgantara
Sehari setelah SOKONG! membuka panggilan terbuka publikasi digital edisi ke-17 pada 13 September 2020, Terasharing Sewon mengadakan sesi wicara seniman bersama Nyoman Vidhyasuri Utami, seorang seniman, penulis, dan pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti dan LaSalle College Jakarta. Pada sesi itu Nyoman Vidhyasuri membahas proses eksperimen yang berkaitan dengan alternative photography process atau yang ia sebut sustainable darkroom. Memasuki sesi tanya jawab dan menjelang akhir pertemuan, beberapa peserta mulai bertanya hal di luar apa yang dipresentasikan, terkhusus menanggapi kutipan biografi singkat yang ditulis di unggahan Instagram Terasharing Sewon yang tertulis, “Sejak awal tahun 2020, ia menjadi anggota Indonesian Art Therapy Community (IATC) dengan kekhususan minat pada potensi dan penggunaan medium fotografi sebagai art therapy.” Perbincangan terkait persinggungan fotografi dengan terapi membuatku tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut. Sayang sekali aku tidak diberi kesempatan oleh jaringan internet untuk bertanya dan ikut berbincang pada saat itu. Sebelum pertemuan berakhir, aku memberanikan diri meminta izin untuk bertanya lebih lanjut ke Instagram @vidhyasuri melalui direct message.
Perkenalan dan pertemuan kami pun berlanjut. Kami berbincang melalui virtual meeting dan aku mencoba untuk merangkum cerita dan hal-hal yang disampaikan melalui tulisan ini.
Nyoman: Jadi gimana? Kamu mau nanya tentang apa dulu nih? Indonesian Art Therapy Community (IATC) dulu?
Abimanyu: Hahaha iya. Bisa gabung IATC awalnya gimana?
Nyoman: Saya bisa masuk dan bergabung karena saya terkategori pendidik atau pengajar, gitu. Jadi ada syarat, selain psikolog, yang bisa join di IATC dan diperbolehkan adalah guru, pengajar. Selain itu juga harus sudah ikutan workshop art therapy yang diselenggarakan oleh Vajra Nirvana, sebuah lembaga konseling di Jakarta. Saya dapat lisensi therapist for art therapy practices dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sesudah ikut workshop itu.
Abimanyu: Jadi IATC itu adalah komunitas yang berisi guru, pengajar, dan psikolog ya?
Nyoman: Yes… yang menjalankan art therapy di profesinya. Jadi dia mempraktikkan prinsip-prinsip art therapy di profesinya. Nah, di psikologi art therapy itu tools, kan ada itu yang hypnotherapy, dll. Nah, ini dia penggunaanya dengan art.
Abimanyu: Bagaimana art therapy dipandang dari kacamata seorang pengajar?
Nyoman: Di art therapy itu ada dua pandangan besar, art therapy yang basisnya seni dan art therapy yang basisnya psikologi. Keduanya agak sedikit berbeda, kendati keduanya bersinggungan. Ada yang berbeda dari keduanya secara epistemologi dan keilmuannya. Yang dari psikologi akan lebih ngulik art therapy untuk terapinya. Sementara kalau yang basisnya seni itu memang art therapy sebagai bagian dari kreativitas.
Abimanyu: Awalnya gimana bisa punya minat pada potensi dan penggunaan medium fotografi sebagai art therapy?
Nyoman: Sebetulnya karena saya ngerasain sendiri. Pada tahun 2018, saya berduka kehilangan mentor terdekat saya. Saya lalu diajak teman saya, seorang psikolog, untuk ikutan workshop-nya Prof. Monty Satiadarma tentang cat air dan emosi. Bagaimana mengekspresikan emosi menggunakan cat air. Workshop sekitar bulan November atau Desember 2018. Sekitar bulan itu juga saya notice ada yang beda dari temperamen saya, jadi cukup lebih mudah marah. Saya enggak ngerti kenapa saya mudah marah. Saya belum bisa mendeteksi bahwa saya sedang ada di kondisi berduka. Belum punya awarenes untuk itu karena memang waktu itu cuma dijalanin sedihnya aja.
Sampai satu titik saya punya rutinitas untuk jalan sore. Entah kenapa saya ngerasa saya harus jalan sore. Jalan aja pokoknya. Aktivitas fisik yang saya perlukan adalah jalan. Jalannya itu bisa minimal 5 km. Lalu saya arahkan semua basis aktivitas harian saya dengan jalan kaki. Sampai di satu titik saya buat ritual jalan pagi dan jalan paginya enggak cuma jalan pagi. Jadi di dekat rumah saya ada Trans Jakarta yang sekali naik itu bisa sampai ke Semanggi. Setiap hari Minggu, saat Car Free Day, saya biasa mengunjungi sebuah taman di Semanggi. Taman yang sebetulnya biasa aja, tapi menurut saya menarik untuk diamati. Saya isi Minggu pagi saya di sana dengan motret, merhatiin arah datangnya cahaya, terus melihat cahaya yang menembus daun-daun, merhatiin segala macam. Aktivitas yang sebetulnya sangat sederhana sih, cuma motret, melihat cahaya, melihat ini bagus atau ini enggak. Menurut saya menarik untuk melihati ranting, daun, tekstur, dan segala macam. Setelah setengah jam berlalu, setengah jam itu sudah berbeda, kebisingan dan beban yang semula ada di kepala kemudian mereda.
Dari pengalaman itu, saya kemudian coba bereksperimen. Bagaimana kalau waktu kondisi pusing saya coba memotret. Bagaimana jika tidak hanya sekadar melakukan aktivitas memotret, tetapi juga melakukan kunjungan ke museum. Waktu saya misalnya punya masalah, ketika marah atau punya emosi yang cukup tinggi kemudian saya ke museum, ternyata melihati barang-barang seni itu bisa “nurunin” emosi, kayak jadi tempat pelarian. Lucu juga museum jadi tempat pelarian. Biasanya tempat pelariannya ke mana gitu, tapi ini ke museum. Kemudian ini menarik buat saya kalau saya bisa menurunkan tensi hanya dengan melihat karya seni atau memotret berarti kemungkinan dia punya potensi nih.

Abimanyu: Aku kira juga karena ada perenungan di sana ya.
Nyoman: Yes, karena salah satu bagian dari healing itu kan refleksi. Permasalahannya di fotografi itu refleksi agak jarang yah, dan refleksi di fotografi lebih kayak, “Eh, like Instagram lu banyak nggak?” atau “Lu ikutan pameran nggak?”. Nah, yang seperti itu tentang hasil lah, lebih ke goals oriented atau money oriented malah, bukan mentingin proses creation-nya. Padahal proses creation-nya sudah bisa jadi sesuatu untuk refleksi, jadi perenungan sendiri, kalau mau.
Sebenarnya awal mulai ketertarikannya ya gitu, dari diri saya sendiri.
Abimanyu: Itu aktivitas jalan sore, pagi, dan memotret itu sesudah mengikuti workshop-nya Prof. Monty ya?
Nyoman: Sesudah. Iya, sesudah.
Abimanyu: Aku sudah mulai cari tahu tentang fotografi di art therapy. Ada banyak istilah yang bagiku asing, seperti photo therapy techniques dan photo therapeutic. Bolehkah diberi penjelasan terkait istilah-istilah itu?
Nyoman: Photo therapeutic itu memang biasanya disepakati bahwa tidak harus berbentuk atau merupakan bagian terapi.
Kalau art therapy yang diajarin sama workshop-nya Vajra Nirvana itu kan memang untuk healing. Untuk penyembuhan kan ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, ada panduannya. Nah, kalau photo therapeutic lebih fleksibel tuh, bisa eksperimentasi, bisa kemudian nggak harus reguler. Kalau dari pengalaman saya, photo therapeutic itu, bisa sesimpel saat mood-nya lagi nggak bener terus langsung motret. Jadi itu sebetulnya lebih kepada kebutuhan pada saat itu, bukan untuk healing. Nah ini ada sedikit berbeda tujuannya, kalau photo as art therapy itu mengikuti prosedur sehingga jadi lebih terarahkan karena ada sesi-sesinya.
Abimanyu: Menjadi formal akhirnya photo therapy itu ya?
Nyoman: Jadinya photo as art therapy itu jadi lebih formal. Kemarin itu ada satu kenalan yang membuat photo therapy, tapi untuk orang berkebutuhan khusus, nah itu ada prosedurnya. Sementara photo therapeutic itu lebih fleksibel.
Abimanyu: Dan di photo therapeutic ini nggak perlu ada therapist atau ahli yang mendampingi?
Nyoman: Sebetulnya jadinya memang ke refleksi ya, merefleksikan si orangnya. Prof. Monty pernah bilang untuk bedakan art therapy dan art activities. Kalau art therapy, kamu sudah masuk konseling, kamu sudah masuk ke satu sistem, kamu sudah masuk ke guided session yang dipandu oleh orang yang memang sudah terlatih atau yang diakui boleh, sementara photo therapeutic itu art activities. Jadi menurutku photo therapeutic adalah art activities yang bisa jadi bahan refleksi, punya efek therapeutic yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik, gitu.

Abimanyu: Katakanlah aku ingin melakukan photo therapeutic. Bagaimana memulainya? Mengetahui yang dilakukan merupakan therapeutic apakah perlu kesadaran?
Nyoman: Kamu kenal Mbak Moeldjanee enggak? Dia kebetulan ikut workshop kuratorial JIPFest 2021 bareng saya. Dia cerita kalau di pagi hari dia merasa “enggak enak”, dia motret dulu selama satu sampai dua jam, sampai kemudian dia merasa mood dan emosinya menjadi lebih baik, baru sesudah itu dia beraktivitas. Sebetulnya dia sudah melakukan photo therapeutic, cuman dia enggak tahu kalau itu photo therapeutic, “Oh…ini berarti ada namanya ya”. Sepertinya banyak banget orang yang melakukan itu, tanpa sadar mereka melakukan photo therapeutic.
Kamu pasti motret karena melihat sesuatu itu indah, lalu kamu senang, kemudian memotretnya. Itu kan bagian dari photo therapeutic. Fotografi yang memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan, merekam momen. Kemampuan itu menjadi bagian dari proses therapeutic. Kegiatan merekam momen yang membuatmu senang atau tenang itu kemungkinan menjadi photo therapeutic.
Sebetulnya kalau di photo therapeutic saya melihatnya lebih ke bagaimana fotografi bisa digunakan sebagai alat yang membuatmu merasa lebih baik. Setiap orang punya ritual yang berbeda, tergantung personality-nya juga apa yang membuatnya tenang. Nggak bisa kalau misal kamu lebih tertarik sama street photography terus dimasukin ke Kebun Raya, disuruh “Lu rileks aja di sini”, tentunya kamu enggak akan bisa serileks kalau misal dilepas di kota, setengah jam, satu jam, atau mungkin bisa berjam-jam. Kamu akan lebih menikmati ketika berada di jalanan kota.
Abimanyu: Kesadaran akan ketertarikan akhirnya menjadi penting ya.
Nyoman: Memang, tergantung referensimu. Ada yang lebih tertarik ke street, ada yang pake still life, bereksperimentasi dengan still life kan juga bisa. Pilih apa yang membuat kamu lebih nyaman.
Ada juga anak yang lebih menikmati ketika memotret fashion karena itu dunianya, membuatnya merasa lebih nyaman dengan dirinya. Ada juga yang mungkin lebih ke praktik eksperimental, seperti melakukan kolase, montase, merajut, dan segala macam. Itu juga menjadi kegiatan yang ekspresif juga. Saya sendiri tertarik sama tumbuhan karena sempat suatu waktu melakukan penelitian tentang itu. Kemudian saya merasa lebih enjoy melihat tumbuhan. Melihat sesuatu yang hijau itu menyenangkan banget di tengah keseharian melihat beton dan segala macam lingkungan perkotaan. Jadi memang tergantung referensimu, kamu lebih tertarik ke mana. Buat saya beberapa orang enggak bisa tuh untuk rileks motret tanaman, karena bisa jadi disuruh memotret tanaman, banyak yang enggak suka, “Ini apaan sih mbak”, jadinya enggak bisa rileks.
Juga kesadaran bahwa memotret bisa membantu kamu menjadi lebih baik, membuat yang tadinya emosional terus emosinya bisa mereda, lebih stabil, lebih manageable. Nah praktik dan ritualnya bisa berbeda-beda. Aku pikir seperti itu.
Abimanyu: Sebagai salah satu praktisi yang aktif di alternative photography process, apakah praktik yang masuk dalam ruang lingkup fotografi eksperimen tersebut juga menjadi bagian dari aktivitas photo therapeutic?
Nyoman: Kalau buat saya, iya. Oleh karena ada unsur meditatifnya dan ada unsur image making-nya. Yang saya lakukan di sustainable darkroom itu rata-rata cameraless, berusaha sedikit mungkin enggak menggunakan klise negatif digital. Karena itu saya rasa apa yang saya lakukan lebih image making. Hasilnya enggak bagus, tapi kemudian dari proses itu ternyata ada hal yang disadari seperti, ketidaksabaran, faktor intensitas cahayanya. Kesadaran itu memunculkan pertanyaan seperti “Kamu sudah sabar atau belum sih?”.
Tapi di satu sisi saya merasa bahwa proses eksperimen yang saya kerjakan itu ada bagian pembuatan image yang memang harus diterima. Kalau kesalahannya diterima yaudah jadi part of that frame. Sudah enggak apa-apa, kalau mau selesai ya diselesaikan, kalau mau ditambah ya silakan. Jadi ada proses jeleknya. Proses yang enggak intended itu kemudian diterima sebagai bagian dari si image itu. Mungkin itu yang kemudian jadi therapeutic bagi saya, bahwa kita belajar terima kesalahannya, bahwa ada “tangan lain”, bukan tangan yang kasat mata ya. Tangan lain yang saya maksud kan bisa cahaya, proses, ketidaktahuan, yang kemudian diterima menjadi bagian dari si foto itu.
Abimanyu: Dan pemaknaan-pemaknaan tersebut kan disadari saat dan sesudah nyetak, seperti kemarin kurang sabar nih, kurang teliti nih. Nah, itu akhirnya dimaknai juga kepada hal-hal di luar proses fotografi kah? Hubungannya dengan keseharian atau mungkin pekerjaan.
Nyoman: Iya, jadi kemudian kalau berhadapan dengan beberapa masalah, pertanyaan yang muncul adalah, sudah sabar belum? Sudah nungguin prosesnya selesai belum? Ini ada bigger picture yang sudah kamu lakuin atau belum? Jadi lebih ke sana ya ditariknya. Karena kita terbiasa ngelihatin foto sebagai sesuatu yang teknikal, you see what you get as a final product. Tapi enggak terlalu ngelihat itu bisa jadi entry point ke sesuatu yang reflektif, ke suatu hal yang lebih besar. Sementara dia punya potensi itu. Potensi yang enggak cuma sekadar “oke dia punya potensi therapeutic, untuk ngebuat aku lebih tenang”, tapi sesudah itu kemudian kamu belajar apa dari proses motret itu, dan apa yang bisa diterapkan di dirimu.
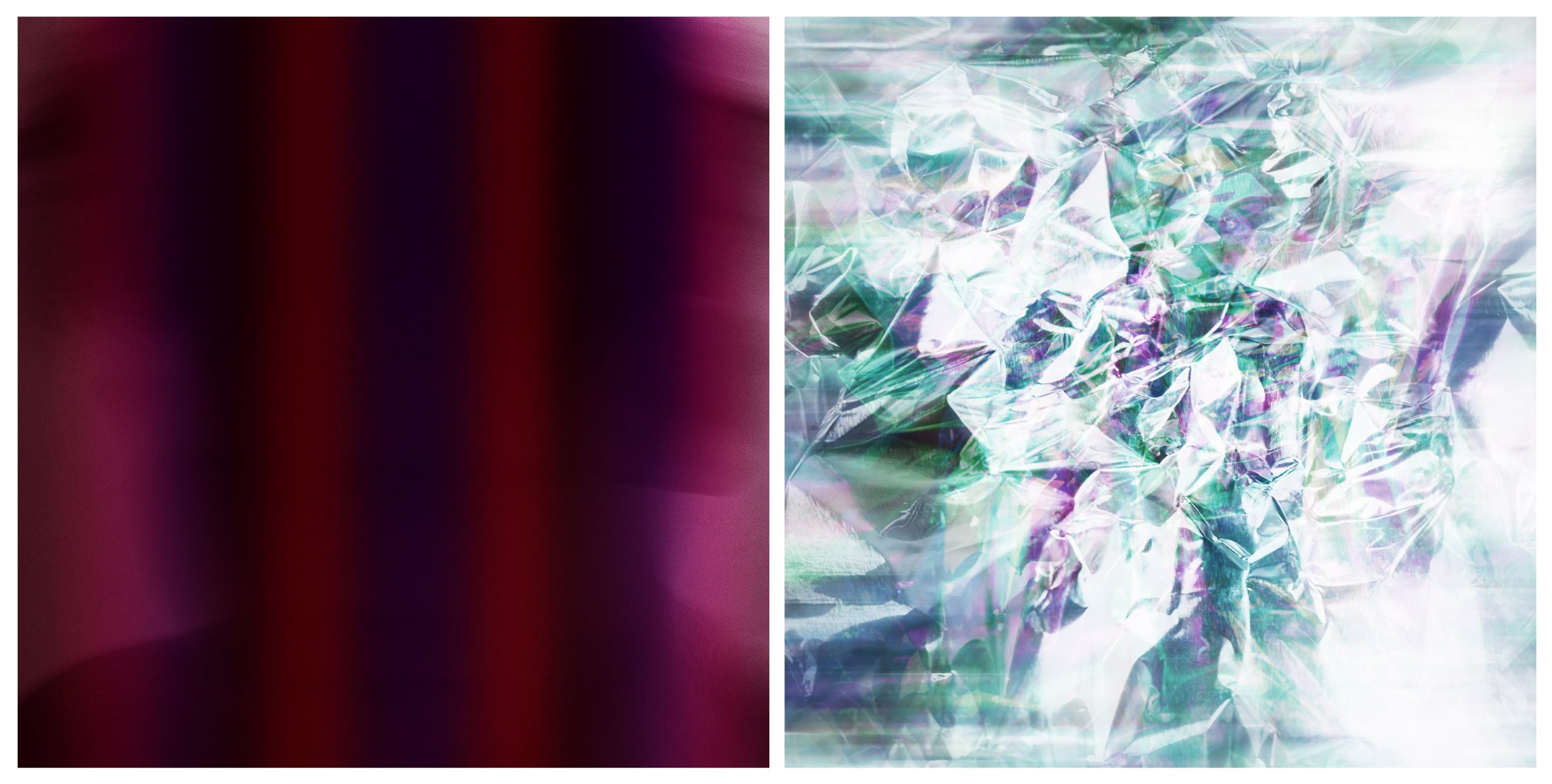
Abimanyu: Kalau misalkan yang dilakukan saat mengampu mata kuliah Studies and Project di Jurusan Fotografi LaSalle College Jakarta itu photo as art therapy atau Nyoman mengajarkan metode photo therapeutic tuh?
Nyoman: Prinsip-prinsipnya adalah prinsip art therapy, tetapi yang dilakukan lebih ke photo therapeutic. Karena sudah tahu ya art therapy itu seperti apa. Di (mata kuliah) Studies and Project itu biasanya saya mulai ada konseling. Kalau normal itu di week ke-3 atau ke-4 perkuliahan. Biasanya pemaparan materi cuma satu jam, lalu dua jam untuk one on one session. Jadi mulai dari kelebihan mereka apa, kelemahan mereka apa, mereka mau lihat project yang akan dibuatnya seperti apa, nah gitu.
Yang menyenangkan dari LaSalle, mereka memperbolehkan, mendukung banget proses eksperimentasi ini, dan ada pantauan psikolog dari bidang akademik LaSalle. Untuk beberapa kasus saya, konsultasi sama psikolog kampus, jadi ngobrol “Oh saya punya kasus di (mata kuliah) Studies and Project saya, pendekatan saya bener enggak?” Jadi emang psikolog kampus itu bisa saya ajak diskusi, tentang mahasiswa/i ini gimana kasusnya, tentang tindak lanjut dan sebagainya.

Abimanyu: Panggilan terbuka publikasi digital SOKONG! edisi ke-17 kan lagi bahas tentang duka ya, aku penasaran dari pengalaman Nyoman terkait menghadapi momen berduka melalui photo therapeutic itu seperti apa? Apa kemungkinan yang bisa ditemukan?
Nyoman: Sebetulnya dari pengalaman saya berduka itu bilangannya tahun. Di satu sisi, masyarakat kita punya ritual ya, seperti 100 hari dan 1000 hari. Karena memang sebetulnya di balik itu tuh mereka sudah punya local wisdom tentang apa yang namanya berduka, dengan harapan bahwa kalau di 1000 hari kita sudah lebih bisa manageable, tidak terlalu emosional saat menghadapi kondisi yang “mendadak”. Berduka kan sebetulnya kondisi yang mendadak ya.
Sebetulnya setiap orang berduka dengan caranya mereka sendiri. Kalau berduka kan ada sesuatu yang kosong kan ya. Kayak di kita tuh ada sesuatu yang kosong dan kita berusaha untuk fill in the gap. Kita berusaha mengisi yang kosong, tapi kan sebetulnya mengisi yang kosong itu karena ada tuntutan bahwa you have to be happy, atau ada tuntutan, ada desakan dari sekitar kita. Susah untuk bilang you have to fill the gap, you have to fill the hole, karena jangan-jangan hole-nya itu dibutuhin sama kamu sendiri. Terus kalau ada kekosongan itu kenapa? Berubah enggak kitanya? Atau jangan-jangan dengan adanya kekosongan itu kita bisa ada refleksi nih, ada hal yang bisa kita pelajari, ada sesuatu yang mendorong kita do something dari yang tadinya enggak mau do anything.
Bagi saya fotografi bertugas di sana, untuk membangun kesadaran. Di tiap orang beda-beda. Fotografi sebagai alat yang sebetulnya bisa bekerja hanya untuk kamu, perorangan. Jawabanmu apa? The answer of your question itu apa? Kan beda-beda. Saya melihatnya seperti itu. Yang lain mungkin bisa melihatnya seperti itu juga, tapi sebenarnya yang menjalaninya mungkin enggak melihat kesadaran yang sama, karena semua situasi dan kondisinya berbeda-beda.
Dan pertemuan virtual kami berlanjut membahas gum bichromate, cerita selama mengajar, pandemi, hingga Alain De Botton dan Stefan Sagmeister.
*Foto-foto yang termuat merupakan bagian dari project yang dikerjakan oleh Freya Florencia, Hans Immanuel, dan Annice Nathania di mata kuliah Studies and Project, LaSalle College Jakarta. Project dalam mata kuliah yang diampu oleh Nyoman Vidhyasuri Utami ini memperlihatkan bagaimana fotografi yang memiliki potensi therapeutic bisa membantu pemulihan seseorang di tengah berbagai persoalan.
